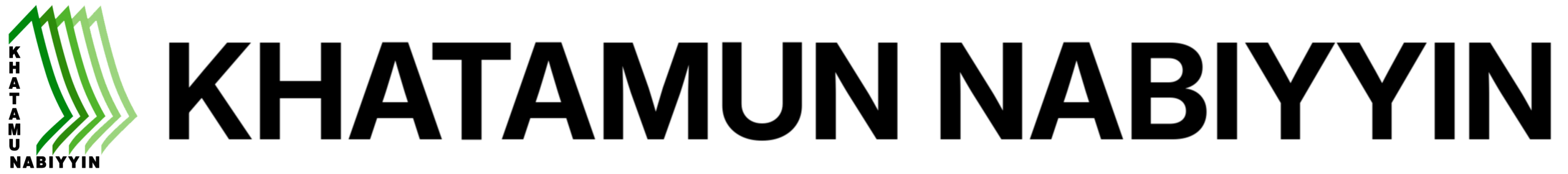Pesantren Hadir di Ruang yang Sering Dihindari
Isu narkotika dan zat adiktif (NAPZA) sering kali ditempatkan dalam bingkai dosa, kejahatan, dan hukuman. Akibatnya, para pengguna lebih banyak dijauhi daripada dipulihkan. Di sinilah pesantren sebagai ruang pendidikan, moral, dan kemanusiaan perlu hadir secara lebih reflektif dan solutif. Kesadaran inilah yang mendorong Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin Jakarta mengirimkan perwakilannya, Muhammad Agus Salim dan Sepy Rizki Amelia selaku pengurus dan/atau pembina, untuk mengikuti kegiatan lokakarya “Pengurangan Dampak Buruk Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) bagi Pemuka Agama”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) di Hotel Kimaya Slipi Jakarta pada 10–14 Desember 2025. Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin menjadi satu-satunya pondok pesantren yang terlibat dalam forum lintas agama ini.
Hingga saat ini, belum tersedia data statistik yang pasti dan terpublikasi secara terbuka mengenai persentase santri pesantren yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Basis data pemerintah maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) belum menyediakan data spesifik yang dapat diakses publik terkait kelompok santri pesantren.
Namun demikian, berdasarkan hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 yang dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,73 persen, atau setara dengan sekitar 3,33 juta orang.
Yang memprihatinkan, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 312 ribu individu usia remaja yang terpapar narkotika. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok usia sekolah, termasuk usia santri di pesantren, berpotensi turut terdampak, meskipun hingga kini belum terdapat data resmi yang secara khusus menjelaskan tingkat penyalahgunaan narkotika di lingkungan pesantren.
Hari Pertama: Mengurai Istilah, Mengubah Cara Pandang
Lokakarya dimulai dengan perkenalan peserta dan diskusi mendasar tentang apa itu narkotika dan zat adiktif. Fasilitator memperkenalkan definisi dari World Health Organization (WHO):
“Zat yang, ketika dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam sistem tubuh, memengaruhi proses mental seperti persepsi, kesadaran, kognisi, suasana hati, dan emosi.”
Definisi ini sengaja dipakai untuk menjembatani beragam istilah narkotika, psikotropika, narkoba, NAPZA, obat, dan zat yang selama ini kerap tumpang tindih secara teknis, etis, dan konotatif. Dalam sesi reflektif, Muhammad Agus Salim berbagi pengalaman personalnya menyatakan: istilah “sabu” pertama kali ia dengar saat masih SD, melalui lagu dangdut populer Sabu-sabu karya Alam S pada awal 2000-an, yang justru membingungkan karena istilah itu dikemas secara ringan. Sejak kecil pula, kata “narkoba” sering dilekatkan dengan dosa dan stigma negatif, bukan dengan pemahaman. Sementara Sepy Rizki Amelia mengungkap pengalamannya bahwa: narkotika hadir di lingkungan keluarganya sendiri dan terbukti merusak diri serta relasi sosial, menjadikannya bukan sekadar persoalan moral, tetapi tragedi kemanusiaan.
Perang Melawan Narkoba: Pelajaran dari Dunia
Diskusi kemudian mengarah pada pertanyaan krusial: bagaimana seharusnya sikap kita terhadap para pengguna? Apakah dengan memerangi dan memberantas, atau menghukumi dan menakut-nakuti, melabeli dan mempermalukan, atau justru merangkul, mengobati, dan memulihkan?.
Fasilitator mengajak para peserta untuk menyimak film dokumenter dari sejarah kebijakan global dalam melihat fenomena menghadapi narkotika. Di Amerika Serikat, dengan slogan “War on Drugs” era Presiden Richard Nixon terbukti gagal: penjara penuh, pasar gelap berkembang, kartel menguat, kekerasan dan HIV meningkat meski kampanye “Dunia Tanpa Narkoba” digaungkan. Sebaliknya, negara Swiss mengambil jalan berbeda dengan harm reduction: perawatan heroin di bawah supervisi medis, stabilisasi hidup pengguna, serta penyelesaian masalah sosial seperti perumahan. Hasilnya signifikan: penurunan kejahatan, HIV, kematian, dan pengangguran.
Hari Kedua: Belajar dari Lapangan, Mendengar yang Jarang Didengar
Pada hari kedua, peserta melakukan kunjungan lapangan ke dua puskesmas di Jakarta Timur yaitu Puskesmas Jatinegara dan Puskesmas Kramat Jati, yang memiliki Poli NAPZA dan layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM).
Dalam sesi tanya jawab yang berlokasi di Puskesmas Kramat jati, Muhammad Agus Salim selaku peserta yang hadir bertanya langsung dengan dokter dan pasien:
“Bagaimana interaksi antar pasien, apakah mereka punya privasi bagi yang ingin ekslusif berobat, serta bagaimana mereka menghadapi stigma negatif dari keluarga dan lingkungannya dan terakhir apakah penting kehadiran peran para pemuka agama dalam proses pengobatan pasiennya?”
Dokter menjelaskan bahwa interaksi antar pasien berlangsung sebagaimana umumnya, tanpa adanya pengelompokan atau pengobatan secara bersamaan. Dalam praktiknya, pasien tidak dikumpulkan dalam satu waktu, melainkan menjalani pengobatan secara bergiliran sesuai kebutuhan masing-masing. Hal ini terutama diperhatikan bagi pasien yang membutuhkan privasi khusus, seperti anak-anak, remaja, dan perempuan.
Bahkan, demi kepentingan terbaik pasien agar tidak mengganggu keberlanjutan pendidikan, dokter menyesuaikan waktu layanan, misalnya pengobatan diberikan setelah jam sekolah selesai, atau pasien diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat dari Puskesmas pusat.
Pengobatan dengan methadone dinilai sangat membantu dalam menstabilkan kondisi pasien. Tidak terdapat batas waktu baku dalam menjalani terapi ini; sebagian pasien tercatat mengikuti terapi selama 10–15 tahun dengan dosis yang terkontrol dan berada di bawah pengawasan medis yang ketat.
Namun demikian, keberhasilan secara medis tidak cukup apabila tidak disertai dengan dukungan sosial dan spiritual, khususnya dari tokoh agama. Peserta kunjungan juga mencatat bahwa pasien menjalani perawatan secara rawat jalan, dan aktivitas ibadah tetap difasilitasi meskipun dalam batasan tertentu.
Diskusi evaluatif pascakunjungan menegaskan bahwa stigma sosial dan kurangnya dukungan dari pemuka agama masih menjadi hambatan terbesar dalam proses rehabilitasi pasien. Temuan ini sejalan dengan kajian empiris tentang PTRM di Indonesia yang menunjukkan bahwa terapi methadone efektif sebagai strategi harm reduction, meski masih menghadapi keterbatasan sarana, SDM, dan dukungan sosial.
Hari Ketiga: Merumuskan Peran Pemuka Agama
Hari ketiga difokuskan pada perumusan peran realistis pemuka agama, di luar kewenangan negara. Peserta dibagi dalam empat kelompok untuk menyusun skema pendampingan, kemudian menghasilkan hasil diskusi dari kelompok empat, yaitu:
1. Sebelum Menjadi Pasien
- Edukasi NAPZA berbasis empati
- Pengakuan bahwa pengguna adalah korban, bukan musuh
- Akses layanan kesehatan dan jaminan hukum
2. Saat Menjadi Pasien
- Konseling spiritual dan psikososial
- Stabilitas emosi
- Perlindungan privasi dan martabat
3. Pasca Pasien
- Monitoring dan follow up
- Pelatihan keterampilan dan kemandirian ekonomi
- Pembentukan komunitas positif
Kelompok Muhammad Agus Salim yaitu kelompok empat menekankan pentingnya mengganti bahasa dosa dengan bahasa pemulihan. Sekali lagi untuk menegaskan bahwa mereka bukanlah pelaku melainkan korban yang harus dirangkul dan dibantu untuk kembali normal.
Kelompok Muhammad Agus Salim, yaitu Kelompok Empat, menekankan pentingnya pergeseran penggunaan bahasa, dari bahasa yang berorientasi pada “dosa” menuju bahasa pemulihan. Penegasan ini dimaksudkan untuk menempatkan individu yang terdampak bukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban yang perlu dirangkul, didampingi, dan dibantu agar dapat pulih serta kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial.
Dari Gagasan ke Aksi: Rencana Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan, peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bentuk aksi konkret yang terbagi ke dalam dua kelompok, dengan target waktu pelaksanaan jangka pendek (3 bulan) dan jangka menengah (6 bulan). Hasil diskusi RTL dari kelompok pertama yang terdiri dari perwakilan agama Islam:
RTL 3 Bulan:
- Kampanye digital edukasi harm reduction,
- Membuat Komunitas digital seperti di Kompasiana,
- Menjalin kerja sama dengan puskesmas terdekat di wilayah tertentu.
RTL 6 Bulan:
- Mengadakan penyuluhan dan edukasi di sekolah atau pesantren,
- Training of Trainers (TOT) di kampus untuk mahasiswa/peer education,
- Kegiatan publik seperti mengadakan fun running.
Sedangkan hasil diskusi RTL dari kelompok kedua yang terdiri dari perwakilan agama Kristen khususnya Protestan:
RTL 3 Bulan:
- Seruan pastoral,
- Kampanye melalui media sosial,
- Layanan hotline service-care.
RTL 6 Bulan:
- Kuliah umum dan seminar/ PWG (public worship gathering),
- Penulisan buku tentang perspektif kristen tentang harm reduction,
- Networking dengan lembaga-lembaga interfaith, BNN, dll.
Lokakarya ditutup dengan Pernyataan Bersama Tokoh dan Aktivis Keagamaan Islam–Kristen, isi salah satu poin terpentingnya:
Mendorong pemuka agama dan kepercayaan untuk lebih terbuka, merangkul, dan memberdayakan pengguna NAPZA di lingkungan pelayanan masing-masing.
Pesantren dan Harm Reduction: Bagaimana dalam Fikih?
Di Indonesia, belum ada fatwa khusus yang secara eksplisit membahas harm reduction dan penggunaan methadone. Hal ini sering menimbulkan keraguan di kalangan pesantren. Namun, kajian fikih kontemporer berbasis maqāṣid al-sharī’ah menunjukkan bahwa pendekatan kesehatan publik dapat dibenarkan. Salah satunya yang diterbitkan Jurnal Metro Islamic Law Review, Vol. 4 No. 1 (2025) yang berjudul: Integrating Maqasid al-Shari’ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy, ditulis oleh Andri Winjaya Laksana, dkk. menegaskan bahwa kebijakan narkotika yang berorientasi pada perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql), termasuk rehabilitasi dan harm reduction, justru lebih selaras dengan tujuan syariat dibanding pendekatan represif semata.
Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Iran dalam jurnal tersebut menunjukkan:
- Indonesia masih dominan punitif,
- Malaysia mengintegrasikan rehabilitasi dan spiritualitas,
- Iran secara pragmatis menerapkan harm reduction (termasuk methadon) demi keselamatan jiwa.
Tawaran Solusi dari Pesantren Khatamun Nabiyyin
Pesantren dapat mengambil posisi strategis dengan:
- Menjadi ruang aman bagi edukasi dan pendampingan NAPZA,
- Mengembangkan fikih sosial berbasis maqāṣid, bukan sekadar halal-haram tekstual,
- Bermitra dengan layanan kesehatan tanpa kehilangan identitas keagamaan,
- Melawan stigma negatif sebagai bentuk dakwah rahmatan lil ‘alamin (Rahmat bagi seluruh alam semesta).
Pesantren tidak perlu menunggu fatwa sempurna untuk berbuat baik. Ijtihad kemanusiaan adalah bagian dari tradisi Islam itu sendiri.
Penutup: Dari Menghakimi ke Memulihkan
Kehadiran Pesantren Khatamun Nabiyyin dalam lokakarya ini menjadi penanda penting bahwa pesantren dapat dan harus hadir di ruang-ruang sulit. Pendekatan harm reduction bukanlah bentuk legalisasi narkoba, melainkan ikhtiar kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga martabat manusia.
Terapi methadone berperan dalam menekan risiko overdosis, penularan HIV, dan kematian secara fisik. Namun, upaya medis tersebut tidaklah cukup. Pasien juga membutuhkan pendampingan keagamaan dan penguatan spiritual, sebagaimana diakui oleh dokter yang terlibat sebelumnya, bahwa dukungan dari pemuka agama juga sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin menyatakan komitmennya untuk siap terlibat secara aktif dan langsung dalam upaya pendampingan tersebut.
Di tengah kompleksitas persoalan NAPZA, pesantren dipanggil bukan semata-mata untuk menyatakan keharaman, tetapi juga untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana cara menyelamatkan manusia secara utuh lahir dan batin?.